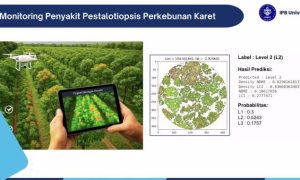Oleh: Muhd Indarwan Kadarisman
(Alumni IPB University)
BOGOR-KITA.com, DRAMAGA – Isu ketahanan pangan di periode pandemi COVID-19 semakin mencuat, dan berbagai negara berlomba untuk mengamankan logistik panganya untuk menghadapi krisis pandemi COVID-19, yang diperkirakan menurut berbagai analisis tentang forecasting COVID-19 ini masih akan panjang.
Dalam upaya mencegah penyebaran pandemi COVID-19, sejumlah negara menerapkan kebijakan lockdown atau pun karantina beberapa wilayah, atau di Indonesia diambil opsi kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).
Pilihan opsi tersebut pada ujungnya akan menganggu pasokan pangan di masing-masing negara. Banyak negara produsen bahan pangan langsung yang membatasai atau bahkan menutup pasar ekspor komoditi tertentu untuk mengamankan kebutuhan pangan dalam negeri. Bahkan FAO dalam releasenya mengatakan, dampak pandemi COVID-19 bisa melumpuhkan berbagai sektor perekonomian, dan memicu terjadinya krisis pangan global di berbagai negera pada rentang April – Mei 2020.
Kondisi ini tentunya akan memicu terciptanya pasar pangan global yang semakin ketat, bahkan negara produsen gandum terbesar dunia seperti Rusia, Kazakhstan, dan Ukraina secara terang-terangan mengumumkan pembatasan ekspor bahan dasar roti. Begitu juga dengan negara Vietna, Thailand yang dikenal sebagai lumbung beras Asia tenggara sudah memikirkan strategi mengamankan pasokan pangan dalam negerinya.
Bagaimana Indonesia?
Kondisi kebutuhan pangan saat ini sebagaimana kita ketahui bersama semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk Indonesia. Namun, ketersediaan lahan semakin menurun dengan adanya kegiatan alih fungsi lahan.
Menurut Hermawan (2011), setidaknya terdapat dua hal yang dapat dilakukan dalam upaya merespon permasalahan tersebut, yaitu: a) mengendalikan alih fungsi lahan pertanian, dan b) meningkatkan kualitas lahan kritis agar dapat berfungsi kembali sebagai lahan pertanian. Opsi kedua yang diusulkan oleh Hermawan (2011) tersebut perlu digalakkan dalam rangka mengantisipasi kegagalan mengendalikan kegiatan alih fungsi lahan untuk kegiatan di luar pertanian. Salah satu alternatif lahan kritis yang berpotensi untuk dialihfungsikan menjadi lahan pertanian adalah lahan pasca tambang.
Lahan pasca tambang merupakan lahan sisa hasil proses pertambangan yang telah mengalami degradasi berupa perubahan fisik dan kimia tanah, penurunan drastis jumlah jenis tanaman baik flora maupun fauna, mikrorganisme tanah, serta rusaknya lapisan tanah karena adanya penggalian.
Lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan produktif seperti pemanfaatan untuk menjadi hutan, pertanian (produksi rumput pakan ternak, tanaman pangan, dan padang pengembalaan maupun untuk konservasi keanekaragaman hayati (Mansur 2013, Kennedy 2002).
Kondisi ini tentunya bergantung pada kondisi klimatologi dan rekonstruksi lahan pada akhir kegiatan penambangan.
Adapun upaya reklamasi lahan pasca tambang terus dilakukan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi hutan, dan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan reklamasi lahan hutan, di mana salah satu indikatornya adalah minimal ada 625 bibit per hektar, dan bibit-bibit yang mati setelah ditanam harus segera disulam kembali.
Lahan pasca tambang sebagai alternatif untuk memproduksi tanaman pangan, perkebunan, pakan ternak ruminansia tentunya memiliki beberapa kendala dan tantangan dibandingkan dengan lahan pertanian pada umumnya.
Husnain et al. (2019) menyebutkan beberapa constrain lahan pasca tambang untuk produksi tanaman pangan di antaranya adalah: tanah miskin hara, sistem irigasi, adanya AAT (air asam tambang), biaya pengadaan pupuk kandang yang mahal, serta isu food savety (keamanan pangan).
Poin food savety menjadi pertanyaan yang sering diajukan karena lahan pasca tambang mengandung logam berat dengan konsentrasi tinggi.
Erfandi et al. (2019) dalam hasil risetnya menyebutkan bahwa pemilihan lahan pasca tambang untuk dijadikan lahan pertanian perlu mempertimbangkan beberapa aspek di antaranya: a) lahan pasca tambang yang tidak akan ditambang lagi, b) lahan pasca tambang yang berada dalam kawasan APL (Areal Penggunaan Lain), c) lahan yang sudah direklamasi selama dua atau tiga tahun, agar lebih stabil, mudah diperbaiki lanskapnya, dan mudah ditata untuk mendia tanam, d) lokasi tambang yang tidak terganggu oleh operasional kegiatan tambang aktif, e) terdapat petani atau kelompok pada areal lahan pasca tambang sehingga ada tenaga kerja yang menggarap lahan, dan f) Adanya kesepahaman antara perusahaan dan pemerintah daerah (Pemda) tentang status lahan dan rencana penggunaan lahan.
Namun begitu, selain beberapa kendala di atas sebenarnya terdapat banyak potensi yang belum dieksplor.
Pertama menurut saya adalah bahwa lahan pasca tambang ini sudah jelas ada dan tersedia, aksesibilitasnya bagus. Semua jalan di tambang itu umumnya sudah terbentuk dan lebarnya bahkan bisa sampai puluhan meter sebab digunakan untuk jalur alat berat.
Kemudian lahan pasca tambang ini juga langsung terhubung dengan pelabuhan atau beberapa sarana transportasi jarak jauh untuk pengangkutan bahan hasil galian tambang.
Topografi di lahan pasca tambang juga lebih mudah diatur, sesuai kebutuhan. Yang dibutuhkan saat ini sebenarnya adalah dukungan regulasi dan teknologi. Apalagi sekarang Presiden Jokowi dalam wacananya ingin melakukan percepatan reklamasi lahan pasca tambang di seluruh Indonesia.
Selain hal di atas, pemilihan jenis menjadi faktor penting untuk keberhasilan revegetasi dan pemanfaatan tanamana pangan yang dipilih, baik itu untuk revegetasi hutan tanaman, maupun untuk pertanian, perkebunan dan pemanfaatan lahan pasca tambang seperti agroforestri, agropremium, dan silvopastura.
Adapun prasyarat pemilihan jenis untuk lahan pasca tambang adalah: tanaman pioner, intoleran, dapat menghasilkan serasah yang baik dan cepat terdekomposisi, memiliki sistem perakaran yang baik, bersimbiosis dengan mikroorganisme tanah, serta bersifat katalik, mudah dan murah dalam perbanyakan, penanaman dan pemeliharaan (Oktorina 2017, Mansur 2013).
Beberapa perusahaan tambang telah menggunakan berbagai jenis tanaman untuk reklamasi lahan pasca tambang, salah satunya adalah kegiatan agroforestri yang dilakukan oleh perusahaan tambang batubara PT Bukit Asam (Persero), Tbk dengan menanam beberapa jenis sayuran seperti, kangkung, bayam, kol, dan kubis.
Terdapat juga konsep agropremium di PT Bukit Asam (Persero), Tbk dengan alternatif tanaman berbuah seperti durian, jambu bol, rambutan dan beberapa jenis tanaman berbuah lainya.
Contoh lain yaitu, PT Inco telah menerapkan plot contoh polikultur cokelat dan tanaman kehutanan lokal dengan nilai ekonomi tinggi.
Contoh di PT Inco (Ambodo 2008), dalam satu 1 hektare (ha) tanaman cover crop berkapasitas untuk pakan 10 ekor sapi pedaging (silvopastura), dan dalam jangka waktu tidak terlalu lama dihasilkan daging sapi potong.
Kotoran sapi digunakan sebagai pupuk tanaman cokelat. Dalam jangka waktu 3-4 tahun (jangka menengah), hasil tanaman cokelat sudah dapat dipanen, dan dalam jangka panjang dapat dipanen kayu-kayu bernilai ekonomis tinggi yang ditanam di antara tanaman cokelat (agoforestri).
Pada tanaman pangan, terdapat beberapa jenis komoditas yang ditanam di lahan pasca tambang, di antaranya adalah jagung, kacang tanah, pepaya, padi gogo, dan cabai.
Padi gogo bisa digunakan untuk cover crop (penutp tanah). Cabai dapat dioptimalkan pada lahan pasca tambang timah (Subiksa et al. 2019).
Sedangkan tanaman perkebunan terdapat komoditas kemiri sunan, serai wangi, dan lada yang berpotensi diusahakan pada lahan pasca tambang timah (Asmarhansyah et al. 2019). Pemanfaatan lahan pasca tambang selayaknya mengarah pada keberlanjutan ekonomi daerah dan masyarakat, tanpa mengabaikan fungsi lingkungan. Dari pemaparan di atas, tentunya potensi lahan pasca tambang dalam upaya menguatkan ketahanan pangan dan memperluas lahan pertanian cukup potensial.
Namun, terdapat beberapa poin kritis yang menjadi perhatian sekaligus tantangan dalam upaya produksi komoditas pangan di lahan pasca tambang. Sejumlah poin tersebut masih dalam upaya penelitian, perbaikan dan mengoptimalkan semua potensi baik dari biaya, regulasi dan kebijakan, aspek-aspek ilmu pengetahuan serta aspek-aspek teknis.
Beberapa aspek yang menjadi fokus sampai saat ini adalah: a) food savety (keamanan pangan), dimana kajian fitotoksisitas logam di Indonesia termasuk masih sangat jarang. Apalagi soal peningkatan pemasukan logam berat ke dalam rantai pengan yang berakibat pada pencemaran pangan. Hasil riset Suastika (2019), tanaman jagung yang ditanam di areal bekas tambang Batubara, Kalimantan Timur menunjukan kandungan beberapa jenis logam berat nilainya lebih rendah dari nilai ambang batas yang dikemukakan oleh Mengel dan Kirby (1987). Kemudian, b) pemilihan jenis vegetasi atau tanaman.
Hal ini memerlukan pengetahuan spesifik tentang jenis-jenis tanaman pangan yang sesuai dengan kondisi lahan kritis pasca tambang, apalagi setiap jenis membutuhkan treatment yang berbeda. Kondisi ini diperkuat dengan kondisi lahan pasca tambang setiap jenis tambang berbeda, lahan tambang batubara berbeda dengan lahan tanbang timah, dan berbeda dengan lahan tambang emas, dll.
Selanjutnya, c) soal varietas unggul dan benih unggul, d) hama dan penyakit, beberapa tanaman pangan yang diujicobakan di lahan pasca tambang rentang terkena serangan hama dan penyakit, seperti penyakit busuk buah antraknisa, dan perangkat hama lalat buah. e) ameliorasi, pemupukan, dan pemeliharaan.
Pertumbuhan gulma di lahan pasca tambang sebenarnya tidak terlalu cepat, namun persaingan unsur hara dengan tanaman utama termasuk tinggi, apalagi dalam konteks tata kelola dan manajemen di lapangan diperlukan usaha yang fokus dan optimal, apalagi jika itu adalah tanaman musiman (pertanian).
Poin terakhir, f) permasalahan, kebijakan dan penerapan reklamasi lahan pasca tambang masih banyak menghadapi kendala. Jika poin ini tidak selesai, maka bagaimana bisa mendapatkan kualitas lahan yang baik.
Upaya reklamasi lahan pasca tambang di Indonesia masih cukup sulit untuk mencapai indikator keberhasilan yang sesungguhnya, jika dikaitkan dengan dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi lahan hutan.
Soal lainya adalah dana reklamasi lahan pasca tambang masih dianggap sebagai cost center, yang diambil dari bentuk persen (%) dari hasil penjualan bahan galian (Mansur 2013). Dibutuhkan biaya cukup besar dalam menata kembali lahan yang telah digali, serta untuk penanaman kembali dan pemeliharaan sehingga terbentuk hutanan tanaman, atau lahan pertanian pangan yang diinginkan.
Komitmen perusahaan di masa awal dalam melakukan reklamasi lahan pasca tambang juga sangat berpengaruh pada biaya yang diperlukan untuk melakukan reklamasi saat ini. Jauhnya jarak antara tanah pucuk dan overburden yang tersedia saat ini dari lahan yang ditambang di masa lalu, juga akan menambah biaya reklamasi.
Tentunya semua poin di atas berkorelasi positif dengan kemampuan memproduksi pasokan pangan di lahan reklamasi lahan pasca tambang.
Sejumlah persoalan tersebut memerlukan masukan dan tanggapan positif dari semua pihak, sebab soal pangan dan alternatif lahan pasca tambang adalah persoalan yang membutuhan integrasi dari berbagai disiplin ilmu, berbagai pengalaman empiris dari berbagai stakeholder, dan integrasi kebijakan dan tata tepat dari pemerintah pusat dan daerah.
Dengan demikian diharapakan tercapai integrasi dan pendekatan solusi untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang melalui optimalisasi lahan pasca tambang di Indonesia.
Tulisan ini memang tidak mendalami soal potensi jenis-jenis komoditas pangan spesifik dan hal-hal teknis dalam penerapanya di lapangan. Tulisan ini hanya mencoba melihat, melakukan pendekatan analisis dan menakar sejauh mana potensi dan risiko alternatif lahan reklamasi pasca tambang untuk dijadikan alternatif lahan pertanian sebagai areal produksi tanaman pangan. []